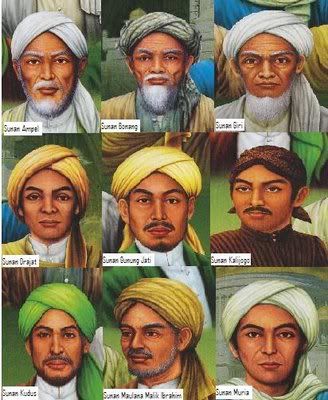Dr. KH A. Mustofa Bisri
This is featured post 1 title
Replace these every slider sentences with your featured post descriptions.Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha - Premiumbloggertemplates.com.
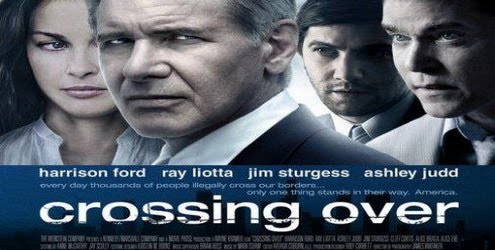
This is featured post 2 title
Replace these every slider sentences with your featured post descriptions.Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha - Premiumbloggertemplates.com.

Selasa, 24 Januari 2012
Kembali Jadi Manusia
Kembali Jadi Manusia
Dr. KH A. Mustofa Bisri
Dr. KH A. Mustofa Bisri
Sudah menjadi rahasia umum, bahwa kehidupan sekarang ini sangat carut marut. Ini disebabkan banyak sudah manusia yang lupa akan qodratnya, sehingga mereka mencintai kehidupan yang penuh dengan tipu daya. Kehidupan manusia sebelum zaman ini tak luput juga dengan segala godaan. Bahkan di jaman Imam al Ghazali pun, para manusia sudah mencintai dunia. Jika imam al Ghazali hidup di jaman sekarang, pastinya kitab yang beliau terbitkan pasti lebih keras, dan lebih sulit untuk kita terima. Kehidupan manusia sangat berlebih-lebihan yang penuh kepalsuan. Manusia sudah lupa kalau dirinya itu menjadi manusia.
Sebenarnya Islam itu sangat mudah jika para manusia tidak gila terhadap kehidupan dunia yang fana ini. Kenapa demikian, karena yang kita ikuti ajarannya adalah juga manusia. Rasulullah merupakan manusia yang paling ngerti manusia itu sendiri. Manusia yang paling memanusiakan manusia. Kenapa manusia sulit untuk mengikuti seorang manusia juga. Apakah kita ini bukan manusia?
Bagaimana seandainya mereka disuruh mengikuti para binatang, kuda misalnya itu kita bisa sakit semua apalagi jika yang diikuti kera yang suka loncat kesana kemari. Nabi Muhammad adalah manusia yang paling manusia. Bahkan Allah Swt, berfirman: “Katakanlah Muhammad, bahwa aku juga manusia seperti kalian.”
Dengan firman diatas, dimaksudkan bahwasanya Rasulullah Saw itu juga manusia seperti kita apa adanya. Punya rasa lapar, haus dan keinginan lainnya. Namun demikian beliau sangat mengerti kebutuhan yang diperlukan, tidak berlebih-lebihan.
Dalam bahasa jawa Rasulullah itu seorang manusia yang undo usoh (mengerti kondisi ruhani) para sahabatnya. Kalau sekolah ibaratnya sekolahan dari paud, TK sampai perguruan tinggi. Rasulullah sangat memahami dengan pasti tingkatan-tingkatan manusia, mana yang tingkatan SD mana yang tingkatan SMP.
Rasulullah tahu persis tingkatan-tingkatan ini, sedang yang kita kaji ini (kitab Minhajul ‘Abidin) adalah tingkatan profesor yaitu ilmu puncak ruhani. Yang sudah tidak takut lagi apa itu neraka dan tidak menginginkan apa itu surga. Yaitu sudah tidak tergoda lagi urusan dunia. Tapi kita saat ini, jangankan bidadari akhirat, bidadari dunia aja kita tidak kuat menahan. Rasulullah Saw, tahu persisi kondisi jamaah dibelakang beliau. Hal ini dibuktikan tidak ada protes dari para sahabat, ketika beliau mengimami jama’ahnya tidak ada yang mengeluh, entah itu bacaan surah yang kepanjangan ataupun yang cepat.
Jangan berlebih-lebihan
Pernah jaman Baginda Nabi ada seorang sahabat dekat yang diutus menjadi duta ke Yaman, yaitu Muadz bin Jabal. Ketika mengimami jama’ah sholat, banyak jama’ahnya yang protes ke Nabi, “Ya Rasul , beliau ketika rokoaat pertama mengkhatamkan surah al-Baqarah, rokaat kedua mengkhatamkan surah an-Nisa’.” Ketika Muadz ditanya oleh Rasulullah, Muadz membenarkan semua itu. Namun apa yang terjadi, Muadz bahkan malah dapat teguran oleh beliau. Karena ada yang berprinsip bahwa semakin panjang bacaan dalam sholat semakin baik, namun ternyata tidaklah begitu ketika kita mengimami jama’ah. “Kamu jangan bikin fitnah Muadz, kamu shalat diikuti oleh orang banyak ada yang tua, muda, ada yangg ditunggu pekerjaan dan macem-macem lainnya. Tapi kalau kamu shalat sendirian di rumah, kalau mau mengkhatamkan al-Qur’an silakan saja. Tapi kalo kamu berani menjadi imam, kamu harus mengerti siapa yang dibelakang kamu.”
Jadi mengikuti Rasulullah itu sangatlah enak, karena beliau adalah manusia yang mengerti akan manusia, dan memanusiakan manusia itu sendiri. Namun lambat laun seiring perkembangan jaman, yang namanya manusia itu sudah berubah, bahkan bukan seperti manusi lagi. Gara-gara hal sepele mertua membunuh mantunya, anak membunuh orang tuanya, sudah tidak manusiawi lagi. Bahkan sekarang banyak pejabat yang mencuri harta rakyatnya, dengan bangganya.
Yang dinamakan manusia itu jikalau tangan kiri sudah megang minuman, tangan kanan megang roti. Coba ditawarkan pisang goreng, maka mereka akan mengucapkan terima kasih. Bagaimana tidak, lha wong tangan manusia itu cuman dua. Lain halnya jika monyet, tangan kiri megang pisang, tangan kanan megang jambu, ketika ditawari roti maka kakinya akan naik. Jadi kita bias melihat, bahwa sebenarnya disekeliling kita ini, ternyata banyak monyet-monyet berkeliaran. Hak-hak orang yang bukan miliknya dia rampas, sepereti serigala dan harimau.
Bersabarlah. Maka kita akan menjadi berat mengikuti kanjeng Nabi yang manusia itu, karena kita tidak terlalu manusia. Maka Imam Ghazali dan yang lain-lain, memberikan dosis tinggi untuk terapi kepada manusia yang sudah tidak manusiawi lagi. Diingatkan kembali, coba kita lihat sebuah pepatah yang berbunyi, “Lebih baik telur hari ini dari pada ayam besok pagi.”
Kenapa demikian, karena manusia tidak mau menunggu hari esok dengan sgala akal pikirannya. Iya kalo besok ayamnya dapat ditangkap, kalo ndak. Mending telur aja yang dimakan,yang keliatan di depan mata
Itu diibaratkan ketidak sabaran manusia dalam menunggu sesuatu. Menunggu ayam besok pagi saja sudah berat apalagi menunggu hari kiamat. Terlalu jauh untuk menunggu pahala yang telah dijanjikan. Jadi memang dibutuhka terapi ruhani tingkat tinggi untuk menyadarkan manusia betapa pentingnya sifat kemanusiaan itu harus tetap terjaga.
Perilaku bukan Asesoris
Kalau kanjeng Nabi itu diibaratkan muara, maka kita perlu melihat lagi ajaran-ajaran yang dibawa beliau secara kaffah. Bukan melihat pakian atau asesoris yang dikenakan oleh beliau. Hanya orang-orang yang tidak mengerti kanjeng Nabi saja, yang mengira itu pakaian Nabi. Coba kita tengok pakaian para petinggi kaum quraisy, seperti Abu Jahal dan lain-lain. Mereka pun menggunakan jubah, sorban, bahkan jenggotnya pun dibikin panjang. Karena yang dikenakan itu merupakan pakaian atau kebudayaan nasional bangsa Arab.
Rasulullah Saw, merupakan manusia yang menghargai kebudayaan, tradisi itu sendiri, sehingga beliau berpakaian seperti itu. Tidak membikin pakain sendiri, meskipun beliau seorang Nabi. Jadi yang dimaksud itba’ kanjeng Nabi itu bukan dari pakaian dan berjenggot, melainkan dari perilkau beliau. Kenapa demikian, Abu Jahal pun juga berjenggot dan berjubah dalam berpakaian, sehingga bisa jadi yang berjubah dan berjenggot itu mengikuti Abu Jahal, bukannya kepada kanjeng Nabi.
Terus apa yang membedakan antara Abu Jahal dan Kanjeng Nabi. Kalo kanjeng Nabi itu wajahnya tersenyum ramah, sedang Abu Jahal itu wajahnya keras (sangar). Maka tergantung pribadi masing-masing, kalo mau beritba’ kanjeng Nabi selain memakai jubah, wajah harusah tersenyum. Kalau wajah yang ditampilkan sangar, maka pastilah Abu Jahal yang menjadi panutan.
Ini bisa kita tengok sejarah. Pada masa Rasulullah Saw ketika ada sahabat yang mau curhat kepada beliau, ketika melihat wajah beliau yang cerah, rasa-rasanya beban yang menimpa mereka seakan-akan telah lenyap. Maka beruntunglah kita yang terkumpul di sini, sehingga dapat mendengarkan pemahaman-pemahaman yang tinggi nilai hikmahnya.
Kalau kita mendengar kisah dari para sufi, maka kita akan dapat berubah perlahan-lahan kembali kesifat manusia kita. Sehingga kita bisa menjalani ibadah dengan benar. Siapapun bisa menjadi abid, tidak harus meninggalkan pekerjaan sehari-hari. Kadang manusia menganggap ahli ibadah itu haruslah hitam dahinya, padahal bukan sama sekali. Banyak sekali manusia yang hanya menurutkan hawa nafsunya. Sehingga tidak lagi mengindahkan Tuhannya, melainkan makhluq yang menjadi Tuhannya.
Dunia ini dahsyat sekali pengaruhnya bagi kehidupan manusia. Surga itu kiri kanannya tidak menyenangkan, sedangka neraka itu kanan kirinya sangat menyenangka (huffatin nar bis syahawat), dan semua yang menyenangkan serta hawa nafsu itulah yang membikin manusia lupa. Oleh sebab itu Rasulullah mengingatkan kepada para manusia agar saling mengingatkan antar sesama. Sehingga tidak terjerumus dalam kesesatan.
Sufi News...
Sabtu, 07 Januari 2012
Mencegat Lompatan-Lompatan GUSDUR
Tinjauan Sufisme Al-Hikam
Oleh: Muhammad Luqman Hakim
Banyak pihak dan banyak cara untuk memahami pola pikir dan spirit KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sejak ia terlibat dalam Jamiyah Nahdhatul Ulama (NU).
Satu-dua pendekatan saja, terutama pendekatan sosiologis empirik, akan “terperangah” oleh hasil final dari realitas gerakan.Gus Dur dalam memimpin NU,atau Gus Dur sebagai pribadi. Kalau toh menggunakan pendekatan komprehensif, maka Gus Dur adalah totalitas ekspresi dari keseluruhan akumulasi NU itu sendiri, baik dari khazanah intelektual, kultural, politik dan harakah organisatoriknya.
Tidak banyak yang meninjau Gus Dur dari dimensi esoterik, sufistik, bahkan perenialistik. Padahal untuk memandang Gus Dur, ucapan tindakan dan manuvernya, harus pula melihat sisi fundamental yang menjadi pijakan spiritualistis Gus Dur, dan tentunya sangat mempengaruhi strategi-panjang pendek, universal-parsial, sakral-sekuler, ideal-real, nasionalisme-internasionalisme, dan sebagainya, bagi kepentingan NU, kebangsaan dan kemanusiaan dunia.
Dengan mengenal lebih dekat “hati” Gus Dus, akan mudah memahami lompatan-lompatan kultural kedepan, sehingga pasca Gus Dur kelak bisa lebih bisa melakukan antisipasi secara visional, tanpa harus membubarkan tatanan yang bertahun-tahun telah distrukturkan dalam piramida besar NU, sehingga para penerus Gus Dur tidak canggung bahkan menemukan spirit optimisme yang “suci” pasca Gus Dur.
Hati Gusdur
Hati Gus Dur adalah “Rumah Ilahi” atau "Arasy Allah”. Rumah yang dipenuhi dengan jutaan dzikiri dan gemuruh musik surgawi, setiap detik, setiap saat, setiap berdiri. bergerak (qiyaman) dan duduk diam (qu’udan) serta ketika tidur dalam kefanaan (‘alajunubihim). Rumah Ilahi selalu terjaga (mahfudz) dari segala godaan duniawi, prestisius, dan segala hal selain Allah, peringatan-peringatan Ilahi dan teguran-teguran-Nya, senantiasa “turun” ketika Gus Dur akan berbuat kesalahan, ketika Gus Dur “frustasi”, ketika Gus Dur terbuai oleh “iming-iming”, atau ketika Gus Dur terlalu bermimpi.
Itulah untungnya jadi Gus Dur, tapi juga demikianlah risiko besar yang harus diterima, manakala Gus Dur menyimpang dan dimensinya, melesat dari Rumah Ilahi, Berat sekali beban Gus Dur menjaga Rumah Ilahi, lebih berat ketimbang menjaga “rumah besar” NU, yang konon sebagai “rumah tua yang berwibawa” ini. Sukses Gus Dur menjaga Rumah Ilahi dalam kalbunya, adalah sukses besar NU. Karena itu di mata Gus Dur sendiri, menurut hati nuraninya - memimpin NU atau tidak, nilainya sebanding. Gus Dur bukanlah tipikal seorang yang berambisi menaiki tahapan derajat duniawi maupun berambisi mendapatkan megamat ruhani-ukhrawi, yang dalam dunia tasawuf disebut dengan al-Murid. Tetapi Gus Dur adalah sosok yang diburu, dikejar dan dikehendaki Oleh tahapan-tahapan tersebut, dicari poleh massa dan organisasi, bahkan secara radikal dalam sufisme ia adalah tokoh yang “dicari Tuhan” (al-Murad).
Gus Dur “dicari” Tuhan, dan ditemukan di lorong-lorong kebudayaan, diketiak orang-orang miskin, dalam aliran derasnya keringat para buruh. Allah menemukan Gus Dur dalam alunan musik klasik, digedung-gedung bioskop dan di tengah-tengah supporter sepak bola. Gus Dur diburu Tuhan, ketika berada disela-sela kolom surat kabar dan majalah, bahkan diburu sampai ke Israel dan Bosnia. Dan Gus Dur “ditangkap” Allah, ketika pandangan matanya sudah setengah buta, ketika merunduk tersenguk-senguk dimakam para Auliya. Sayang, Allah memeluk Gus Dur ketika Gus Dur sudah “gila”, dan memimpin arisan orang-orang yang “gila” kepadanya.
Benar kata Khalil Gibran, "Di tengah masyarakat yang terdiri dari orang-orang gila, orang yang paling waras disebut sebagai orang yang paling gila. Dan di tengah masyarakat yang terdiri orang-orang yang waras, orang yang paling gila disebut orang waras".
Gus Dur dikatakan "gila" oleh masyarakat gila yang merasa waras. Dan ia disebut sebagai paling waras ditengah-tengah orang-orang "gila" yang tidak ingin waras. Kebudayaan "gila" dewasa ini harus diatur oleh orang paling waras, walaupun orang paling waras itu harus mendapatkan sebutan sebagai orang paling gila.
"Kegilaan" Gus Dur adalah tipikal paling relevan untuk memimpin masyarakat yang tergila-gila oleh kegilaan. Sebab Gus Dur adalah terali, tembok, pilar, atap, dan ornamen-ornamen bagi rumah Ilahi, yang terus mengalami "keterasingan" di tengah-tengah rumah besarnya sendiri, di tengah¬tengah bangsanya sendiri, juga di sudut-sudut lapuk warga nahdhiyin-nya.
Dia Sendiri Adalah Al-Hikam
NU sebenarnya adalah organisasi paling banyak jumlah kaum 'arifin-nya dibanding organisasi keagamaan yang lainnya. Karena itu NU memiliki derajat sebagai satu-satunya organisasi "Yang Diridhai", atau mungkin yang lain sekedar diakui, disamakan, atau "terdaftar" saja dalam catatan lembaran langit.
Kehadiran Gus Dur untuk mereformasi secara puritan melalui "Khittah 1926" adalah bentuk perenialisme NU dalam matra zaman yang lebih luas. Bukannya upaya memutar gerak jarum jam sejarah ke masa Ialu. Tetapi, mundur untuk melompat ke depan lebih jauh. Lompatan-Iompatan dalam visi Gus Dur ketika menerjemahkan Khittah 1926, merupakan lompatan "spiritual NU" yang kemudian berakses kepada lompatan moral, politik, kebudayaan dan tradisi intelektual serta sosial-ekonomi. Lompatan-lompatan ini bisa dilihat dari dimensi paling sederhana, namun merupakan dimensi paling dalam. Yakni dimensi sufisme yang menjadi "akhlak" ulama salaf dan ulama-ulama generasi pendiri NU.
Hal yang tidak bisa dipungkiri, adalah kesatuan para ulama pendiri NU dan Gus Dur sendiri, dengan wacana-wacana Corpus Tassawuf yang ditulis oleh Taajuddin Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Atba'illah as-Sakandari, yakni kitab Al-Hikam. Hampir seluruh pesantren salaf di Indonesia, mengkaji kitab tersebut, dan sekaligus menjadi pijakan moralitasnya.
Kitab Al-Hikam, merupakan magnum corpus kaum sufi, yang mengandung mister-misteri spiritual dan sekaligus bisa digunakan untuk memprediksi gelombang pasang surut spriritual keagamaan semacam. yang terjadi dalam tubuh NU, Gus Dur sendiri yang hafal di luar kepala setiap wacana (matan) kitab Al-Hikam ini, tentu memahami secara lebih massif dan universal bagi kepentingan historis NU. Dalam bahasa yang paling "tradisional" kembali ke Khittah 1926, berarti kembali ke dalam dimensi "Al-Hikam" tersebut. Karena itu sebelum memimpin NU, Gus Dur telah menyatu dengan "Al-Hikam", yang kelak ketika memimpin NU, Al-Hikam menjadi instrumen "penggugat" dalam intern NU. Sayangnya, ribuan pesantren di Indonesia dewasa ini, telah merasa asing dengan kitab ini. Sebab, kitab ini merupakan kitab instrospektif, kitab yang bisa menusuk diri sendiri, kitab yang "ditakuti" oleh para kiai. Akhirnya, dari 6.000 pesantren yang ada, hanya beberapa gelintir saja yang masih mengkaji kitab ini. Fakta ini pula yang membuat gerakan moral ulama yang dilakukan Gus Dur banyak terhambat.
Matan Al-Hikam, Khittah 1926 dan Pasca Gus Dur
Coba kita renungkan sukses besar para. pendiri NU ketika mendirikan NU tahun 1926. kesuksesan ini erat dengan matan pertama dari Al-Hikam:
"Di antara tanda bersiteguh terhadap amal, adalah berkurangnya harapan (kepada Allah) ketika terjadi tindakan dosa".
Para Ulama pendiri NU dan Gus Dur tidak pernah mengajak warganya untuk bersikap menggantungkan diri pada upaya dan amalnya, dengan asumsi bahwa amal itu bisa menyelamatkannya. Kerj a organisasi, perjuangan, aktivitas nadhiyin, harus terjauhkan dari sikap i'timad terhadap amal. Sebab, sikap i'timad seperti itu, hanya melahirkan ketamakan dalam organisasi dan ambisi historis. I'timad terhadap amal, ikhtiar, dan upaya-upaya manusiawi hanyalah bentuk "penghalang" antara hamba dengan Sang Khalik. Amal hanyalah makhluk, bukan Khalik. Membanggakan makhluk adalah bentuk immoral yang jauh dari harapan spiritual yang menghantar sukses besar.
Para mujahid di kalangan ulama NU yang turut menghantar kemerdekaan bangsa ini, sama sekali menepiskan ketergantungannya terhadap amal dan sejarah. Satu-satunya tempat i'timad hanyalah Allah. Karena itu Khittah 1926 dulu jauh dari rekayasa-rekayasa ambisi politik, kalau toh pun ada akan tersingkir oleh sejarah. Ibnu Atha'ilah mengaitkan kebergantungan terhadap amal tersebut dengan tindakan dosa. Dalam konteks Khittah 1926, kembali ke Khittah 1926, tidak harus disertai "rasa bersalah" yang terus menerus, sehingga mengurangi optimisme masa depan (raja') itu sendiri. Sebab siapa pun yang merasa "miris" dan pesimis terhadap rahmat Allah ketika ia berbuat dosa, berarti ia belum bergantung kepada Allah, masih bergantung kepada amalnya. Begitu juga, warga NU yang masih merasa bersalah atas "dosa sejarah" yang mengakibatkan dirinya ekslusif, tersingkir, pesimis, dan bahkan cenderung "membangkang" berarti masih i'timad terhadap upaya amal, bukan i'timad kepada Allah. Sikap demikian inilah yang ingin "diberantas" Gus Dur.
Fakta demikian sesuai dengan wacana Al-Hikam berikutnya:
"Keinginanmu untuk tajrid, sementara Allah masih memposisikan dirimu pada dimensi sebab akibat (duniawi) merupakan bagian dari nafsu tersembunyi. Dan keinginanmu kembali pada sebab akibat (duniawi), sementara Allah sudah memposisikan dirimu dalam dimensi tajrid, merupakan penurunan (degradasi) dari cita¬cita yang luhur. "
Tajrid merupakan bentuk eskapisme kepada Allah tanpa menghiraukan dimensi selain Allah. Dalam konteks ke-Gus Dur-an, adalah "tidak mau tahu" urusan organisasi, urusan kemasyarakatan, urusan kemiskinan dan kebudayaan, bahkan urusan demokratisasi. Sikap demikian merupakan bentuk eskapisme nafsu yang tersembunyi, bukan eskapisme kesucian Ilahi. Padahal mayoritas warga NU belum sampai ke tahap tajrid ini. Lebih ekstrim lagi banyak tokoh-tokoh NU menggunakan baju tajrid untuk kepentingan pribadinya, kepentingan nama dan perutnya, ya kepentingan nafsunya. Lebih jauh lagi untuk kepentingan. politik kelompok tertentu.
Sebaliknya, mereka yang sudah sampai pada maqam tajrid dalam konteks ke-NU-an- tiba-tiba masih berambisi terjun ke dunia kausalitas NU. Tentu , tindakan demikian merupakan degradasi moral bagi ketokohannya. Para tokoh yang seharusnya “pensiun” dari NU, untuk lebih mendekatkan diri dalam “wilayah muraqabah dan taqarruh Ilahi”, ternyata banyak yang "cawe-cawe" ke dunia empirik, yang membuat keruwetan di tubuh NU. Padahal Allah sudah memberikan "kursi empuk spiritual", malah memilih kursi empuk duniawi. Inilah agenda Gus Dur sampai saat ini. Bahwa transformasi dari tahap kausalitas menuju tahap tajrid dalam NU, adalah tahap perjuangan dari unsur kepentingan menuju unsur "kepentingan Ilahi", dari hal-hal yang bersifat empirik ke esoterik. Sukses besar NU manakala NU mampu melakukan transformasi menuju "tajrid" peradaban yang luhur.
Matan. Al-Hikam. selanjutnya adalah:
"Tercapainya cita-cita tidak bisa mengubah dinding takdir"
Gagalkah Gus Dur? Gagal dan tidak, harus ditinjau dari prespektif yang luas. Ditinjau dari segi Al-Hikam, keberhasilan Gus Dur dengan Khittah 1926, bukan karena Gus Dur atau para pendukungnya. Hakikat keberhasilan Gus Dur yang ada, sama sekali tidak takdir Ilahi terhadap NU.
Ikhtiar, upaya, semangat, jihad, adalah "tanda-tanda" sukses NU, bukannya faktor penentunya. Dalam dimensi tasawuf Al-Hikam, apabila NU ditakdirkan berhasil dan sukses, akan banyak Gus Dur lain yang memiliki visi dan ruh yang sama. Bukan sebaliknya.
Namun kenyataannya, justru sebaliknya. Banyak tokoh-tokoh NU yang merasa mampu mengubah takdir Allah, dan ketika berhasil menganggap sebagai upayanya sendiri tanpa campur tangan Ilahi. Kecuali kalau gagal, baru mengatakan, “Demikianlah takdir Allah…!”
Karena itulah, Al-Hikam menyarankan pada matan selanjutnya:
"Abaikanlah dirimu untuk ikut campur (urusan Allah), sebab apa yang sudah diurus oleh. selain dirimu berkakaitan dengan dirimu, Anda jangan ikut campur di dalamnya untuk kepentinganmu."
Selanjutnya Gus Dur pun sering menghimbau kepada para kiai dan ulama, khususnya kalangan NU, agar tidak ikut mencampuri urusan yang bukan bidangnya. Misalnya urusan pencalonan presiden maupun gubernur, ataupun bupati. Urusan tersebut ada yang berwenang menangani. Ikut campur di luar bidangnya adalah bentuk salah kaprah yang fatal, dan menjadi kerumitan dinamika NU. Dan matan berikutnya berbunyi:
"Ijtihad Anda pada hal-hal yang sudah dijamin untuk diri Anda, dan sikap teledor Anda terhadap kewajiban yang harus Anda penuhi, merupakan bukti atas kekaburan mata hati Anda."
Bayangkan, berapa ribuan tokoh-tokoh NU yang mata hatinya kabur, karena etika dan sikap moralnya yang teledor, hanya karena mementingkan tuntutannya dibandingkan mementingkan tugasnya?
Gus Dur tidak pernah putus asa. Walaupun ia di tuntut terus menerus, khususnya pada setiap even dan momen tertentu. Gus Dur hariya bisa kembali sebagaimana wacana Al-Hikam dari matan ke matan berikutnya.
Dan sungguh, matan-matan Al-Hikam, tertib dan strukturnya, mulai awal hingga akhir, yang memenuhi lembaran-lembaran kitab, merupakan kesimpulan dari perjalanan spriritual penempuh jalan sufi, sekaligus juga peristiwa-peristiwa dalam konteks NU yang bakal maujud dalam sejarah NU dan umat Islam, Karena itu membaca NU pasca Gus Dur akan sangat mudah dengan membaca Al-Hikam dengan penafsiran dinamika NU,' karena di sana penuh dengan solusi-solusi langsung dan aktual.
Dalam prediksi matan Al-Hikam, NU pasca Gus Dur adalah pertama-tama NU akan melewati perebutan-perebutan ambisi yang saling menyodorkan alternatif. Sedangkan alternatif yang disodorkan oleh Khittah 1926, sebagai visi Gus Dur, dianggap belum tuntas. Padahal Gus Dur, sebagaimana Al-Hikam, menyandarkan titik akhir sejarah NU hanya kepada “alternative yang terbaik menurut Allah”, alternatif konsepsionalisasi yang direkayasa atau dipaksakan menurut penilaian tarbaik manusia. Kapan dan bagaimana allternatif Ilahi NU teraktualisasi dalam sejarah. Menurut Gus Dur dan Al-Hikam, hanya Allah saja yang tahu kapan aktualisasi historis idealisme itu maujud secara proporsional.
Paling tidak, Gus Dur walaupun belum maksimal telah melampaui tiga matan Al-Hikam di atas, dalam konstelasi ke-NU-annya. Tugas pelanjut Gus Dur adalah menerjemahkan matan-matan berikutnya dan konteks spirit NU masa depan, melalui solusi yang ditawarkan oleh Al-Hikam. Dalam hal ini, sangat dibutuhkan suatu Syarah Al-Hikam yang konstektual dengan NU modern. Suatu tantangan bagi kaum spiritulis NU yang memiliki "kearifan" dalam sejarah.
Sebagaimana para pembaharu atau mujtahid dalam dunia Islam, pasca mujtahid adalah para komentator, interpretator, dan kreator yang lebih spesialis dan detil. Maka, pasca Gus Dur, adalah Gus Dur-Gus Dur "kecil" yang "cantik" dan "indah" yang mampu mengepakkan sayap-sayapnya menjadi tarian yang rampak. Tarian "Gusduriyah".
Diantara Jalan Sufi Gusdur
Oleh: KH.M. Luqman Hakim
Kharisma Gus Dur, setelah wafatnya, ternyata melebihi realitas kehidupannya. Keharuman spiritual yang eksotis, begitu lekat dan fenomenal. Hal ini tentu berhubungan dengan kondisi sosiologis
masyarakat NU yang seringkali membuat standar maqom spiritual seseorang diukur dengan kharisma dan keanehan yang luar biasa (khariqul ‘adat) berupa karomah-karomah, walau pun dalam perspektif Sufisme standar tersebut tidak baku.
Dalam khazanah tasawuf, tradisi kewalian seseorang sangat ketat dengan aturan-aturan gnostik (ma’rifatullah) yang teraksentuasi dalam sikap ubudiyah. Ada dua model kewalian dalam sosiologi Tasawuf, di satu sisi seorang wali ada yang sangat popular dengan hal-hal luar biasa di luar jangkauan nalar, ada pula yang sangat tersembunyi, bahkan kehebatan karomahnya tidak dikenal oleh public sama sekali.
Namun, Gus Dur memiliki fenomena spiritual yang langka dibanding kiai-kai lain di Jawa, karena harus muncul dalam gebrakan sejarah yang penuh warna. Dari sosoknya sebagai budayawan, seniman, kiai, politisi, pemikir, pembaharu, dan seorang yang mampu mengangkat khazanah tradisional dalam dialog cosmopolitan yang actual. Dan spirit yang membawa sosoknya sedemikian kuat itu, dilandaskan pada spiritualitas yang sangat kaya dengan kebebasan, kemerdekaan, penghargaan kemanusiaan, sekaligus askestisme yang tersembunyi dalam jiwanya: Dunia Sufi.
Sufisme Gus Dur yang selama ini hanya difahami oleh massanya, melalui kebiasaan ziarah ke makam para wali, ungkapan-ungkapan yang controversial, dan spontanitasnya yang inspiratif, serta garis keturunan seorang Ulama dan wali yang terkenal, Hadhratusy Syeikh Hasyim Asy’ari, pendiri NU. Namun, laku Sufistik Gus Dur justru terletak pada sikap dan konsistensinya terhadap nilai-nilai tasawuf yang sama sekali tidak terpaku pada simbolisme tasawuf sebagaimana gerakan kaum Sufi modern saat ini.
Komunikasi Ilahiyah yang selama ini terjalin adalah “hubungan rahasia” yang sunyi di tengah-tengah hiruk pikuk dunia, dan melakukan gerakan terlibat dengan kehidupan nyata, dengan keberanian mengambil resiko bahaya, demi mempertahankan prinsip utamanya. Namun di sisi lain, ada konser kebahagiaan yang berirama indah dalam musikal dzikrullah, saat Gus Dur sedang sendiri, menyepi (khalwat) dalam jedah kesehariannya. Dua sisi hiburan spiritual yang boleh disebut sangat langka: Ramai dalam sunyi, dan sunyi dalam ramai.
Pengaruh dari nuansa yang diyakini itu, Gus Dur justru mampu melakukan terobosan yang luar biasa, begitu cepat. Dalam 20 tahun gerakan Gusdurian, masyarakat NU yang jumlahnya begitu besar terbuka lebar dalam dialog kemodernan, seperti sebuah gerakan konser musik yang dinamik. Maka liberalitas tradisionalnya muncul dengan kuantum melebihi zamannya. NU menjadi organisasi masyarakat muslim modern yang mengejutkan, yang disebut oleh Nakamura sebagai organisasi Islam paling demokratis di dunia.
Namun seluruh dinamika gerakan Gus Dur tidak lepas dari nilai-nilai tradisional Sufistiknya yang transformative. Semisal Gus Dur yang begitu kental dengan hikmah-hikmah Ibnu Athaillah as-Sakandary yang tertuang dalam kitab Sufi Al-Hikam – bahkan hafal di luar kepala – dalam membangun masyarakat Islam dalam konteks ke-Indonesiaan.
Kitab Al-Hikam sangat dikenal oleh para Ulama Sufi sejak abad tujuh hijriyah, menjadi manual bagi “Sufisme Pesantren” tingkat tinggi, sebagai kajian sufi paska Ihya’ Ulumaddin, Al-Ghazaly, Ar-Risalatul Qusyairiyah karya Abul Qasim Al-Qusyairy, maupun Al-Luma’, karya Abu Nashr as-Sarraj.
Kekentalan Gus Dur dengan Al-Hikam memberi warna kuat, terutama dua wacana disana yang berbunyi: “Janganlah engkau bergabung atau berguru dengan orang yang kata-kata dan perilaku ruhaninya tidak membangkitkan dirimu dan menunjukkan padamu menuju Allah.” Konon, nama Nahdhatul Ulama mendapatkan inspirasi dari hikmah tersebut, sekaligus menjadi standar apakah Ulama NU kelak konsisten dengan kebangkitan menuju Allah atau menuju dunia?
Kemudian, hikmah lain yang begitu kental, adalah, “Pendamlah dirimu di tanah sunyi, karena biji yang tak pernah terpendam tidak akan tumbuh dengan sempurna.” Sebuah wacana yang sangat kuat tekanannya dalam menggugat kemunafikan beragama, dan segala gerakan industri ekonomi dan politik atas nama agama, yang akhir-akhir ini begitu menguat beriringan dengan gerakan formalisme keagamaan.
Menyembunyikan hubungan antara hamba dan Allah sebagai rahasia kehambaan adalah mutiara Sufi yang agung. Sebaliknya pamer pengalaman beragama, bahkan menjurus pada riya’ adalah bentuk syirik yang tersembunyi. Karena itu, dalam Al-Hikam juga disebutkan, “Nafsu dibalik maksiat itu nyata dan jelas, tetapi nafsu di balik taat itu, sangat tersembunyi, dan terapi atas yang tersembunyi sangatlah sulit.”
Hal yang amat tidak disukai oleh Gus Dur manakala menjadikan agama sebagai industri ekonomi maupun politik. Agama yang sacral, memang harus dijaga oleh politik, tetapi politisasi, apalagi menciptakan agama sebagai dagangan bisnis adalah melukai agama itu sendiri.
Agama menjadi murah, dan agama menjadi duniawi, bahkan agama ditukar dengan kepentingan nafsu yang sangat memuakkan.
Langganan:
Postingan (Atom)